Almira tertegun. Ia memandangi langit mendung yang berwarna abu dari jendela kamarnya. Rintik hujan menghujani semesta. Burung-burung saling berlarian di atas, terbang ke sana kemari mencari tempat untuk berteduh. Pepohonan menjadi basah, jalanan basah, tetiba kedua pipinya ikut basah. Bukan sebab air hujan, melainkan air matanya sendiri.
Ia mengusap kesedihannya sesaat. Langit berwarna abu-abu yang pekat di atas sana, masih awet warnanya. Menjadikan jalanan senyap, hening, tak banyak manusia yang berlalu lalang di luar.
“Aku harus bagaimana sekarang?” ucapnya lirih sembari memandangi nilai raportnya, yang baru saja ia terima dua minggu lalu. Nilai Almira di atas 90. Giat belajar, membuatnya berhasil di semua mata pelajaran. Pun, ia selalu memperhatikan dan selalu fokus ketika ada guru yang menjelaskan. Ditambah, ia memiliki kebiasaan membaca buku di hari-hari luangnya.
Air matanya masih saja keluar. Isak tangisnya mulai kentara. Ketika ia menatap bingkai foto ibunya. Iya, ibunya telah tiada. 5 tahun yang lalu. Di saat Almira masih duduk di bangku SMP. Ibunya menderita kanker ovarium stadium 3. Tidak ada yang menyangka, Ibunya memiliki sebuah penyakit yang cukup mematikan itu. Ditambah, tidak ada biaya yang cukup, agar Ibunya mendapatkan perawatan yang lebih baik.
Almira sendiri, masih menyesali kepergian Ibunya. Dia selalu berandai-andai. Semisal, ia tidak pergi dari rumah. Semisal, dia mengetahui penyakit Ibunya lebih awal. Mungkin, Almira akan lebih lama di rumah. Membantu Ibunya. Mengajak Ibunya bercerita lebih lama. Juga, mengajaknya tertawa girang di beranda rumah.
Di suatu malam yang hening. Ibunya pernah bertanya kepadanya, “Almira sayang, kelak ketika Almira sudah besar, Almira mau jadi apa?”
Almira menggelengkan kepalanya. Saat itu ia baru saja memasuki bangku SMP. Dia masih belum tahu ingin menjadi apa nantinya. Dia hanya menatap kedua mata Ibunya yang berbinar, menyaksikan sinar rembulan yang saling menyemburat indah.
“Bu, lihat ke atas sana. Bulannya indah,” pekiknya girang, menatap panorama langit yang indah.
Ibu menahan rasa sakitnya malam itu. Almira masih belum menyadari. Ibu berusaha menanggapi ucapan Almira barusan.
“Iya, Nak. Indah sekali, ya....,” sahutnya, dengan menahan rasa sakit yang luar biasa.
“Ibu, kenapa ?” tanya Almira yang memalingkan pandangan ke arah Ibunya sekarang.
“Ibu tidak apa-apa, Nak,” ucap Ibu bohong.
Untuk itulah, setelah Almira mengetahui penyakit Ibunya, pun kepergian Ibunya yang meninggalkan perasaan getir itu. Almira bertekad ingin menjadi seorang dokter obgyn. Ia ingin sekali, menyelamatkan banyak nyawa. Agar para perempuan yang persis dengan penyakit Ibunya, bisa sembuh dari penyakit yang ia derita. Meskipun, tidak banyak memiliki harapan.
Maka, bila ditanya oleh para guru di sekolah. Atau pun Ayahnya. Ia bisa menjawab dengan lantang dan berani. Perihal impian yang selalu ia idam-idamkan.
“Cita-citamu ingin menjadi apa, Almira ?” ucap Ayahnya di pagi yang dingin.
“Dokter Obgyn, Yah..., Almira mohon. Dukung sepenuhnya, cita-cita Almira yang ini, ya...,” Almira mengangkat wajahnya ke atas. Sehingga binar pada kedua matanya terlihat jelas.
Terlihat jelas raut wajah mengerut. Senyumnya tak selebar tadi.
“Nak..., apa tidak ada impian atau cita-cita kamu yang lainnya lagi ?”
“Tidak ada, Ayah. Lagi pula, menjadi dokter adalah impianku mulai sekarang. Aku hanya ingin menjadi penyelamat bagi banyak orang di kemudian hari. Aku tidak ingin, apa yang dialami Ibu, dialami oleh orang lain, Ayah,”
“Tapi, Nak...,” Ayah mulai mendekat. Memeluk Almira dengan dekapan hangat.
“Apakah Ayah mampu, menyekolahkanmu di sekolah kedokteran. Gaji Ayah di kantor swasta, hanya-“
“Ayah..., Tolonglah.” Almira mulai melepas pelukan hangat itu. Hatinya sedikit tersentak.
“Ayah..., apakah salah bila aku menginginkan menjadi seorang dokter ?” tanya Almira dengan suara yang bergetar. Kedua matanya mulai memerah.
“Tidak ada yang salah dengan semua itu, Nak. Ayah tahu, impian kamu begitu baik. Namun, kondisi kita tidak cukup baik, Nak.” Mendengar itu, Almira tak bisa lagi membendung kesedihannya. Ia memasuki kamarnya. Menutup rapat-rapat pintu kamarnya. Dan menumpahkan kesedihannya di atas kasur.
“Apakah aku harus merelakan impian besarku ini ? Lantaran gaji Ayah tak sebesar itu?” gumamnya merenungi nasibnya. Kedua matanya kian memerah. Ia kemudian, melihat tumpukan buku di atas meja. Pun nilai rapot semester akhirnya. Ia sembunyikan semuanya di dalam lemari lusuhnya yang penuh debu.
“Kenapa, nasib sial terus menghantuiku. Semesta telah merenggut Ibu, sekarang mau merenggut mimpiku, aku tak percaya ini,” cercanya seolah menyalahkan keadaan.
Pikirannya menjadi kacau. Hatinya tidak bisa tenang. Raganya kian kisruh.
“Kalau aku gagal melanjutkan ke jenjang berikutnya, apakah itu artinya, aku juga gagal di dalam pencapaian hidupku ? Apakah aku akan bernasib sama, seperti Ibuku ?” sambungnya disertai dengan isak tangis yang belum mereda.
Dulu, Ibu begitu mencintai melodi musik. Kedua tangannya piawai memainkan piano. Banyak piala berjejal di atas rak lemari, hingga tak muat menadahi. Sebab, Nenek tidak memiliki cukup uang untuk menyekolahkan Ibu di sekolah musik. Ibu mengubur mimpi besarnya. Mendapatkan beasiswa pun masih tak cukup untuk memenuhi kebutuhan Ibu juga biaya sekolah, serta peralatan pianonya. Sehingga, Ibu memilih untuk menikah dengan Ayah. Dan melupakan semua mimpinya.
Almira paham, bila Ibunya sering meratap sendirian di tengah malam. Di saat sinar rembulan merekahkan cahaya indahnya. Ibu duduk melamun di beranda. Sembari menggerakkan jemarinya, seolah memainkan piano. Ibu memejamkan kedua matanya. Sehingga ia kalut di keheningan malam. Almira hanya menatapnya dari balik pintu yang kendor engselnya. Lalu, Ibu mengeluarkan bulir air matanya. Pun, bila ditanya “Ibu sedang apa ?”
“Ibu sedang menikmati keindahan malam, Nak...,”
Almira meratapi nasibnya seharian di dalam kamar. Ia juga tidak ingin bernasib sama dengan Ibunya. Ia ingin menunjukkan kepada Ibunya di surga, bahwa ia bisa melalui ujian berat ini.
Maka usai wisuda SMA. Almira bertekad keras mencari informasi beasiswa. Tidak peduli sudah berapa lama ia menatap layar ponsel, juga menghabiskan waktu seharian di dalam kamar untuk membaca buku. Ayah masih menatapnya heran. Sesekali, Ayah mengecek tabungan di bawah kasur yang ia sisihkan sedikit untuk Almira.
“Ini masih sedikit, betapa keras kepalanya dia. Kenapa tidak menikah saja, urusan menjadi beres,” ujar Ayahnya, lalu menghela napas.
Almira masih bersikeras. Usahanya menampakkan hasil. Ia menemukan beasiswa yang cocok dengannya. Tanpa pikir panjang Almira mencoba mengirim berkas-berkasnya ke sana. Dan ketika pengumuman telah tiba. Dia ditolak. Tentu saja, ia meratap seharian lagi di dalam kamarnya. Sembari memandangi langit malam yang indah.
“Bagaimana sekarang, kenapa sia-sia usahaku ?” gerutunya mulai cemas.
Lagi-lagi terbersit kenangan tentang Ibunya. “Aku pasti bisa,” ucapnya macam orang kerasukan. Sehingga, berhari-hari ia makin mengusahakan kerja kerasnya. Lalu, mengirim berkas-berkasnya ke universitas lainnya. Seminggu kemudian, hasilnya keluar. Kedua matanya seolah tak percaya dengan apa yang ia saksikan.
“Selamat Anda dinyatakan ‘Lolos’,” ia berteriak cukup kencang. Ayah bangun, menghampiri kamarnya.
Ekspresi Ayahnya datar. Lalu berkata,”Bagaimana dengan biaya administrasi dan lain-lainnya, Nak. Ayah sudah bilang, gaji Ayah pas-pasan.”
Suasana berubah menjadi masam. Padahal, ia sudah begitu yakin. Bahwa, di masa depan ia akan berhasil, dan tak bernasib sama dengan Ibunya, yang harus merelakan semua mimpinya.
“Pasti bisa, Yah..., aku tidak akan menyerah. Untuk kali ini aku ingin menggapai apa yang aku impikan.” ucapnya penuh percaya diri.
Ayah menunduk. Menyaksikan temaram lampu yang mulai redup. Almira tersenyum lebar, sembari berkata dalam hati,” Impianku, jangan hilang dulu. Aku pasti bisa menggapaimu,”
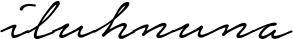




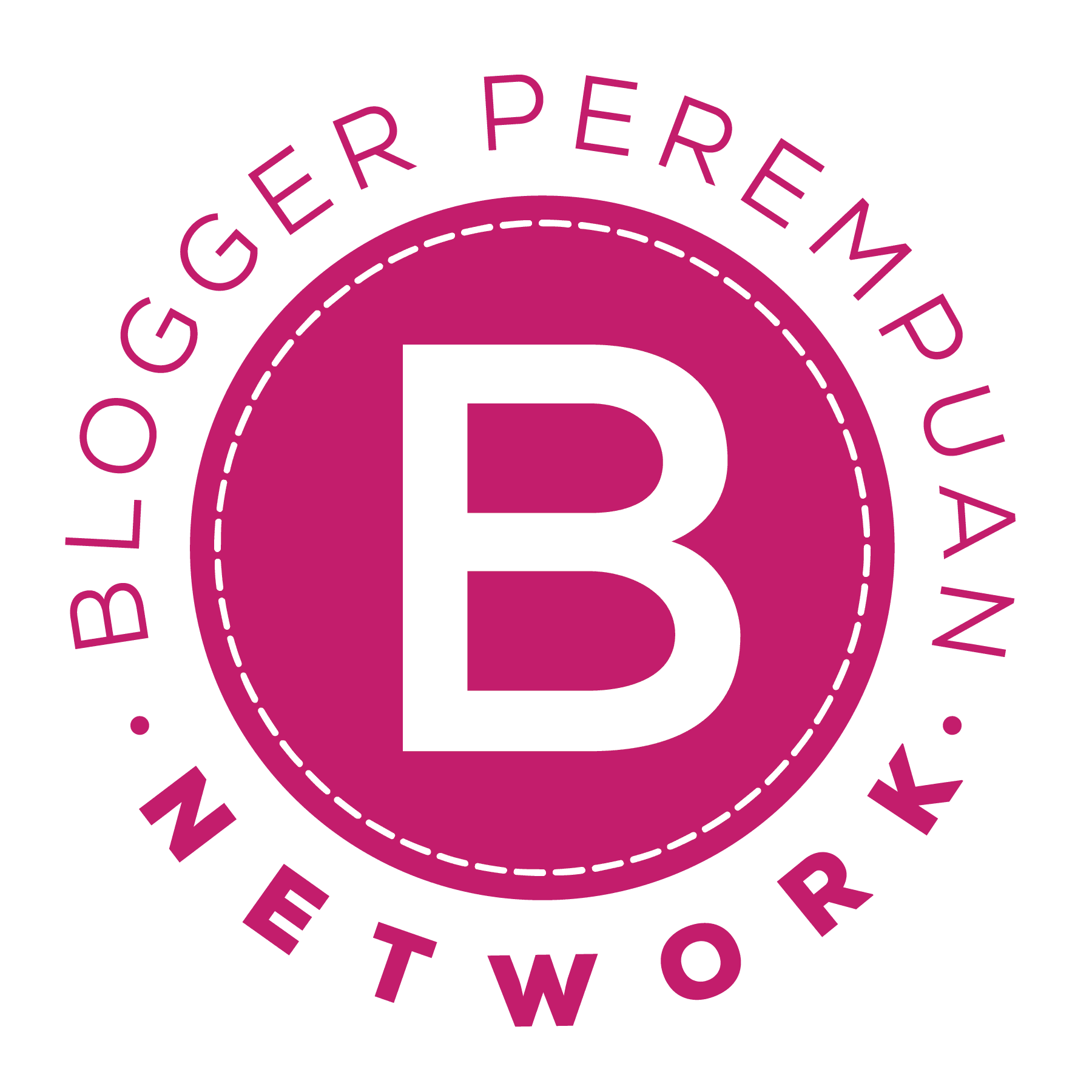


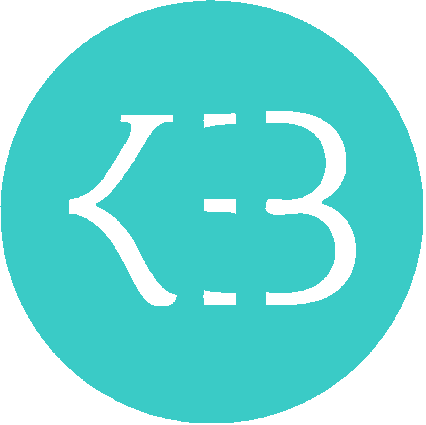

🥺❤️
BalasHapus